Saya hobi makan. Apalagi makanan baru atawa makanan yang belum pernah saya lihat dan rasakan. Meski perut saya belum lapar, namun mulut seakan selalu menuntun untuk diberi sentuhan asin, manis, atau pedasnya makanan yang saya jumpai. Setiap melihat makanan baru, air liur saya selalu tumpah (hanya kiasan saja hehe..). Bahkan saking ngilernya, berapa pun uang yang akan dikeluarkan rela saya rogoh dalam-dalam dari saku hanya untuk melepaskan rasa penasaran dan kegilaan saya dalam mencicipi makanan asing.
Suatu malam, seusai mengantar pacar, iseng-iseng saya berjalan menelusuri jalan raya Cilegon. Hari sudah maghrib. Sambil mencari-cari masjid untuk sholat maghrib, mata selalu jelalatan melihat kain-kain khas warung pinggir jalan seperti pecel ayam dan lele yang banyak bertebaran di daerahku, Serang, Banten. Sampai setelah kaki agak pegal, mata saya tertuju pada sebuah warung bertuliskan “Nasi Uduk dan Tempe Mendoan”. Warung yang hanya beratap terpal dan berdinding kain bertuliskan menu-menu yang ada di warung tersebut. Beberapa detik otak saya berputar mencoba mengingat dimana saya pernah mendengar dan tahu nama tempe mendoan. Kalau nasi uduk, disini sudah sangat familiar. Tempe mendoan sepertinya pernah saya kenal sebagai nama makanan khas sebuah daerah di Indonesia. “Tapi daerah mana?” begitu kira-kira pertanyaan yang terlitas dalam hati. Untuk beberapa saat saya hanya bolak-balik warung pinggir jalan itu tanpa masuk dan langsung mencicipinya. Rasanya kurang afdol kalau pertanyaan tempe mendoan tidak terjawab sebelum memakannya.
“Tempe mendoan, kan makanan khas daerah Purwokerto!” tiba-tiba melompat begitu saja jawaban dari kepala saya. Ya, itulah jawabannya. Selain dikenal daerah bermakanan kripik, Purwokerto, Jawa Tengah, juga masyhur dengan tempe mendoan-nya. Saya juga baru ingat kalau pengetahuan saya tentang tempe mendoan baru saja saya dapatkan kira-kira seminggu sebelum pertemuan saya dengan warung itu dari sebuah features di Koran Kompas.
Ditarik oleh rasa penasaran ingin mencoba, kaki saya gerakkan memasuki warung yang memiliki panjang kira-kira hanya empat meter tersebut. Padahal perut saya masih agak kenyang malam itu. Sholat maghrib terpaksa saya tunda. Lagian saya belum menemukan masjid di sekitar situ.
Di bangku yang telah tersedia, sudah ada beberapa orang sedang asyik menikmati makan mereka. Air liur saya langsung meminta jatah melihat mereka. Saya duduk agak menjauh dengan mereka yang sudah dari tadi berada disana.
Seorang perempuan, penjaga warung bertanya, “Mau makan, Mas?” Tentu saya meng-iya-kan. Tangan perempuan itu langsung dengan gerakan yang sudah terlatih mencomot beberapa potong tempe goreng dekat penggorengan dan meletakkannya di atas sebuah piring kaca kecil. Ia hanya memberikan itu.
Lalu nasi uduknya? Ia hanya menunjukkan letak dimana nasi uduk berada dengan matanya. Tepat di depan mata saya--juga di hadapan semua pembeli—nasi uduk sudah ditumpuk sedemikian rupa. Bungkus nasi uduk memakai daun pisang yang terlihat sangat eksotis dibanding dengan kertas rames. Nampaknya pemilik warung sengaja menaruhnya disana agar memudahkan pembeli mengambilnya. Para pembeli tinggal ambil saja seberapa banyak mereka mau.
Pertama-tama, saya amati tempe di depan saya. Inikah yang dinamakan tempe mendoan? Hanya tempe biasa yang diselimuti tepung lalu digoreng. Tempe yang biasa saya lihat di tukang gorengan cireng, bakwan, kroket dan risol. Tidak ada yang istimewa tampaknya. Berarti selama ini saya telah mengenalnya. Hanya tidak tahu kalau itu bernama tempe mendoan.
“Tidak. Ini beda! Ini tempe mendoan asli Jawa Tengah, sedangkan tempe yang biasa kamu makan hanya tempe-tempean. Imitasi!” batin saya mencoba membesarkan dan tdak ingin mengecewakan keinginan saya semula yang ingin memakan makanan khas Jawa Tengah itu. Saya juga tidak sempat bertanya karena pemilik warung sedang sibuk melayani yang lain. “Nanti saja tanyanya setelah makan,” batin saya.
Akhirnya saya santap tempe mendoan dengan penuh gairah beserta nasi uduk. Dan ternyata memang rasanya biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Rasanya sama seperti tempe-tempean yang sempat saya remehkan tadi.
Tempe di piring ternyata berjumlah enam. Perut sebenarnya sudah terasa amat penuh dengan memakan tiga potongnya. Namun karena pengunjung yang datang dahulu tadi menghabiskannya, saya berkesimpulan: porsi itu memang porsi yang ditetapkan bagi semua pengunjung dan tak bisa dikurangi. Saya ber-hipotesa berapa pun tempe mendoan yang dimakan, harga tetap sama enam biji tempe mendoan. Saya sendiri tidak mengerti dari mana analisa gila itu saya dapatkan.
Setelah menghabiskan enam tempe mendoan dan dua nasi uduk, perut terasa sangat kenyang. Lalu saya membayar. Mendapat kesempatan berbincang, saya bertanya memenuhi rasa penasaran apakah yang saya makan tempe mendoan atau tempe-tempean.
“Tempe mendoan-nya yang mana, sih, Mbak?”
Perempuan itu menunjuk tempe yang telah habis di atas piring saya. Oo...jadi benar ini adalah tempe mendoan.
“Makanan khas mana, Mbak?” tanya saya lagi sambil berharap jawaban yang diberikan adalah apa yang saya harapkan.
“Ya...makanan sekitar sini saja,” jawabnya kalem. Ia tidak tahu kalau saya yang mendengar kecewa. Ternyata tempe mendoan yang saya makan adalah tempe-tempean. Bukan tempe mendoan asli Purwokerto, Jawa Tengah, tapi tempe asli Cilegon, Banten.
Lalu bagaimana namanya bisa sama persis: sama-sama bernama mendoan? Mungkinkah ada silsilah tempe mendoan dari Purwokerto dengan tempe mendoan Kota Cilegon masa dulu? Atau tempe disini hanya duplikat dari tempe mendoan di Purwokerto? Atau sebaliknya? Saya belum dapat menemukan jawabannya sampai sekarang. Tapi kata seorang teman yang asli Cilegon, di kota yang terkenal dengan bajanya ini, ada desa yang namanya sama dengan daerah asal tempe mendoan, yakni Purwakarta. Hanya beda huruf a dan o saja. Apa nama desa ini juga ada hubungannya? Lagi-lagi saya belum menemukan jawabannya. Terlepas dari mana yang dahulu dan terakir ada, dan mana yang mempengaruhi dan dipengaruhi, makan malam di warung piggir jalan di Kota Cilegon sangat menarik. Sambil menikmati santapan malam, kita bisa menyaksikan kendaraan lalu lalang.
Saya jadi teringat saat makan lesehan di Jember bersama teman. Bedanya, disana kita makan lesehan, disini kita makan di atas bangku.
Cilegon, 10 Januari 2008
Tulisan ini pernah gue kirim ke Rubrik Gado2 di Femina. Tapi mpe sekarang gak tau tuh nasibnya. Kayaknya seh ditolak. Kalo dimuat kan pasti ada wesel dateng ke rumah dong ya hehee
Rabu, 10 Desember 2008
Tempe Mendoan Apa “Mendoan”?
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

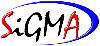
 RSS Feed (xml)
RSS Feed (xml)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar