Ada adagium yang cukup populer dalam dunia pendidikan. Bunyinya: attoriqotu ahammu minal maadah, (penguasaa) metodologi lebih penting ketimbang (penguasaan) materi. Artinya, cara menyampaikan (baca: mengajar) materi itu lebih penting dari materi itu sendiri. Tapi benarkah selalu begitu?
Cara guru menyampaikan materi dalam suatu bidang pelajaran memang menentukan apakah materi akan sampai dengan baik kepada peserta didik atau tidak karena masing-masing peserta didik memiliki kelebihan dan kelemahan dalam menangkap informasi (pelajaran). Maka, ahli pendidikan mengklasifikasikan cara belajar individu dengan visual, auditorial, dan kinestetik. Dan masing-masing cara belajar ini memiliki kecenderungan yang berbeda dalam menangkap materi dengan penyampaian yang berbeda.
Namun, meski digaris bawahi, bahwa kemampuan menyampaikan materi ini sebelumnya telah didahuli oleh penguasaan materi. Karena kalau tidak akan kacau.
Perdebatan monolog
Jum’at (23/10) lalu, seorang teman yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) bercerita tentang guru bahasa Indonesianya yang kurang “memuaskan” saat mengajar.
Menurut pengakuannya, hampir setiap mengajar pelajaran bahasa Indonesia teman ini selalu mengulum senyum karena penjelasan yang diberikan sang guru tidak sesuai dengan yang ia tahu. Tidak pas. Lain.
Bijaknya—karena alasan rasional bahwa guru yang mengajarnya adalah seorang perempuan dan khawatir malu—teman ini diam saja tak mau mendebat dan memprotes penjelasan gurunya yang rada beda dengan pengetahuan secara umum. Kasihan kalau didebat, begitu katanya.
“Kalau gurunya laki-laki saya akan berdebat habis,” tambahnya kemudian.
Saya penasaran. Lalu bertanya apa yang keliru dari yang diajarkan gurunya itu.
Teman SMA ini bercerita suatu saat ketika sang guru menjelaskan materi teater.
“Dalam teater mesti ada dialog. Mesti ada yang ngobrol. Jadi, jumlah minimal pemain teater adalah dua orang karena kalau lebih sedikit dari itu dialog tidak bisa terjadi,” kata teman ini menirukan ucapan guru bahasa Indonesia.
“Kalau monolog bagaimana?” tanya saya.
“Iya padahal di buku ada itu, Kang,” katanya kepada saya, “pointer yang menjelaskan bahwa monolog sebagai bagian dari teater,” lanjutnya. Kemudian ia tertawa.
Saya tersenyum juga mendengar penjelasan “baru” itu.
“Trus monolog apa dong menurut guru kamu?” tanya saya penasaran.
“Monolog adalah ngomong sendiri...”
Dalam hati saya memotong dan membenarkan pernyataan gurunya itu tentang monolog. Tapi kemudian saya tercengang saat teman SMA ini melanjutkan, “Tapi monolog hanya dipakai saat latihan teater. Bukan saat main teater,” begitu katanya menjelaskan uraian gurunya. Lalu ia tertawa terbahak. Terdengar melecehkan sebetulnya.
Pengetahuan teman ini tentang sastra—meski masih muda—tidak bisa dibilang main-main. Juga dalam seni pertunjukan, teater. Ia sering bergumul dengan pertunjukan-pertunjukan teater bahkan pernah beberapa kali menonton pertunjukan teater (salah satunya monolog).
Maka, wajarlah jika teman SMA ini hanya cengar-cengir mendengar penjelasan gurunya yang kurang “sreg” tentang teater.
Pendidikan guru
Keesokan harinya, di koran Kompas, ada sebuah berita mengagetkan saya: banyak guru tak pantas jadi guru. Dalam berita hard news itu, terungkap bahwa banyak guru yang sebenarnya belum layak menjadi guru profesional karena pendidikan mereka masih rendah. Ada yang masih diploma, bahkan masih lulusan SMA. Padahal pemerintah sudah menetapkan bahwa guru mesti berpendidikan minimum D-IV atau strata satu (S1).
Saya kemudian teringat pada sosok guru Bahasa Indonsia teman saya itu. Saya teringat penjelasaanya tentag teater. Tentang monolog.
Saya tak tahu apakah guru bahasa Indonesia teman itu lulusan SMA atau perguruan tinggi karena saat saya bertanya, ia juga tidak tahu gurunya lulusan mana. Yang pasti, guru bahasa Indonesia itu belum menguasai materi. Bisa dibayangkan bagaimana murid-murid yang ia ajar menjawab soal-soal bahasa Indonesia yang berkaitan dengan monolog di Ujian Nasional nanti.
Di saat profesi guru diberi tempat yang terhormat dan diberikan “iming-iming” sejahtera oleh pemerintah (karena banyak juga guru yang belum benar-benar merasakan) apalagi yang sudah sertifikasi, mestinya guru terus memperbaiki kualitas. Banyak membaca karena saat ini pengetahuan mudah didapat. Apalagi di era Google ini.
Saat (hapir) semua informasi bisa didapatkan dengan meng-klik Google—pengetahuan bisa dengan cepat didapat—jangan sampai guru malah kurang up date ketimbang murid dalam hal pengetahuan kontemporer. Memang ini tugas berat. Tapi guru tentu tak boleh kalah dengan murid. Apalagi mengajarkan hal keliru.
Jangan sampai guru yang sejak dulu biasa diakronimkan (sosok yang mesti) digugu dan ditiru menjadi (figur yang) meragukan untuk ditiru.
Kamis, 24 Desember 2009
GURU (raGu untuk ditiRu)?
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

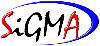
 RSS Feed (xml)
RSS Feed (xml)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar